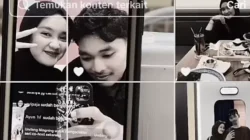Udara di Yan, negeri bertanah subur di pinggir Laut Andaman, pagi itu lembab dan tenang. Daun-daun kelapa berayun pelan, seolah ikut menyambut langkah pelan seorang peziarah yang baru turun dari mobil. Pakaian gamis putihnya sedikit tertiup angin. Di tangannya tergenggam tasbih yang ia pegang erat sejak berangkat dari Aceh.
Dialah Tgk. Nanda Saputra, putra Pidie yang pagi itu memijakkan kaki di Meunasah Sentui, Kampung Aceh, Yan, Kedah, Malaysia. Tanpa iring-iringan protokoler. Tanpa mikrofon. Hanya sebuah niat suci yang ia bawa: berziarah ke makam Teungku Chik Oemar Diyan, ulama besar Aceh yang jasadnya terbaring jauh dari tanah kelahiran.
Di antara batu nisan yang sederhana, Tgk. Nanda yang juga Ketua Pergunu Pidie duduk bersimpuh. Air matanya jatuh perlahan. Sunyi menyelimuti, seolah seluruh dedaunan pun ikut diam. Ia tahu, ini bukan sekadar ziarah. Ini adalah ziarah sejarah. Ziarah ke luka lama yang perlahan ingin dijahit kembali.
Lebih seabad lalu, Teungku Chik Oemar Diyan mengambil keputusan yang berat. Ketika kolonialisme Belanda mencengkeram bumi Aceh, beliau memilih hijrah. Bukan karena takut. Tapi karena dakwah dan ilmu harus tetap hidup, meski jasad harus menjauh dari kampung halaman.
Beliau membawa serta anaknya, Teungku Abdul Hamid. Mereka menyusuri laut, menyeberangi batas, dan akhirnya menetap di Yan, tempat yang saat itu menjadi persinggahan banyak ulama Aceh. Di sinilah ia melanjutkan misi: mengajarkan al-Qur’an, fikih, dan hikmah-hikmah kehidupan kepada generasi baru. Di sinilah, jasadnya kini terbaring dalam diam, namun ilmunya tak pernah padam.
Tgk. Nanda sosok kandidat doktor itu menengadahkan tangan. Suaranya pelan, serak. Ia membaca surah Yasin dan menghadiahkan al-Fatihah kepada arwah sang ulama pengembara. Di sekelilingnya, hanya pohon dan langit yang menjadi saksi. Namun dalam hati, ia tahu bahwa ziarah ini telah menyambungkan kembali tali silaturahmi yang nyaris putus.
“Beliau ini bukan hanya ulama Aceh,” katanya lirih kepada penduduk setempat yang menemaninya. “Beliau adalah bagian dari sejarah besar Islam di Asia Tenggara.”
Wajah-wajah tua di Kampung Aceh mengangguk. Mereka masih mengingat cerita dari nenek moyang tentang “Teungku Aceh” yang datang membawa cahaya ilmu. Cerita yang bagi mereka bukan dongeng, melainkan warisan yang dijaga.
Di antara pusara, Tgk. Nanda berdiri. Pandangannya menerawang jauh, seakan menembus waktu. Ia membayangkan bagaimana Teungku Chik Oemar Diyan mengajar anak-anak Melayu sambil menyeka peluh. Ia membayangkan malam-malam panjang yang dihabiskan sang ulama untuk menyalin kitab dengan tangan gemetar. Ia membayangkan betapa rindu ulama itu pada tanah Aceh—namun memilih bertahan demi ilmu yang terus mengalir.
“Beliau adalah contoh bagaimana ulama tidak terikat tempat,” ujar Tgk. Nanda. “Mereka hidup untuk misi. Dan misi itu terus hidup dalam kita.”
Langit mulai mendung. Gerimis kecil turun membasahi nisan. Tapi tak ada yang beranjak. Seorang pemuda lokal yang baru mengenal sosok Teungku Chik itu dari cerita Tgk. Nanda terlihat mengusap mata. Ia tidak menyangka bahwa orang Aceh dulu pernah mengajar di desa kecilnya.
Ziarah ini sederhana. Tidak ada kamera TV. Tidak ada selebaran. Tapi justru dari kesederhanaan itulah makna lahir: bahwa sejarah bukan untuk dirayakan dengan gegap gempita, tapi untuk direnungkan, diserap, dan diwariskan.
Tgk. Nanda membawa pulang lebih dari sekadar dokumentasi. Ia membawa semangat. Bahwa ulama Aceh pernah melintasi batas-batas politik dan geografi demi menanamkan nilai-nilai Islam. Bahwa kita adalah penerus tugas itu. Bahwa sejarah bukan masa lalu, tapi jalan panjang yang harus terus ditapaki.
Dalam perjalanan pulang, Tgk. Nanda menyimpan sejumput tanah dari sisi makam. Ia tidak menyimpannya sebagai jimat, tapi sebagai pengingat. Bahwa perjuangan tak selalu pulang ke rumah. Kadang ia harus wafat jauh, agar ilmunya menyebar lebih luas.
Ziarah ini bukan titik akhir. Ini adalah awal dari serangkaian perjalanan lainnya: menghubungkan kembali jejak-jejak ulama Aceh di Malaysia, Patani, Mekkah, hingga Hadhramaut. Jejak yang selama ini tersembunyi di balik lipatan peta dan kabut sejarah.
Dan di tengah sunyi kapal yang membawanya kembali ke Pidie, Tgk. Nanda menulis satu kalimat dalam catatannya:
“Dalam diam pusara itu, aku mendengar suara yang lantang: teruskan jalan ini, anak muda. Jangan berhenti di batas kenangan.”[]